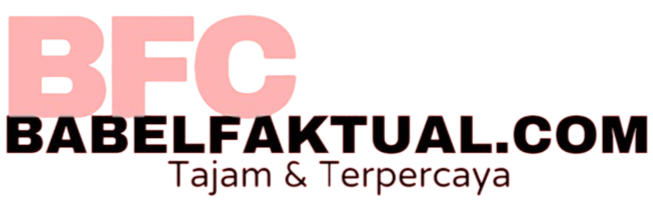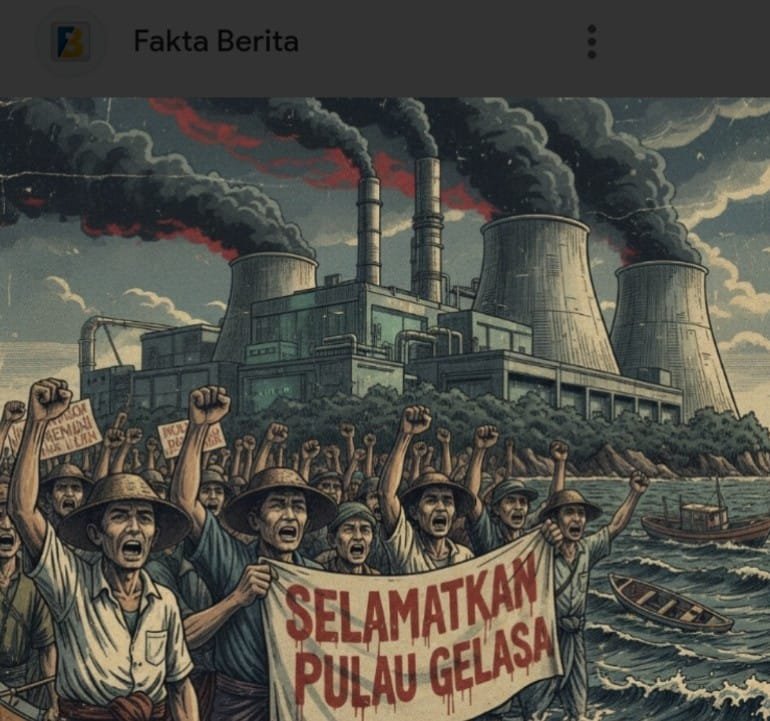BFC, PANGKALPINANG— Belakangan ini publik disuguhkan berbagai tulisan dan kampanye yang mempromosikan energi nuklir sebagai solusi masa depan Indonesia.
Banyaknya artikel pro-PLTN tersebut menempatkan energi nuklir sebagai simbol kemajuan, bagian dari diplomasi energi global, sekaligus jawaban atas menurunnya pasokan energi fosil.
Sekilas, narasi itu terdengar ideal dan menjanjikan. Namun, di balik citra ilmiah dan argumen strategis yang disajikan, terdapat sejumlah hal yang patut dikritisi.
Sebab, promosi pro-nuklir di Indonesia tampak tidak lagi murni bersifat akademik, melainkan sudah menyentuh ranah pembentukan opini publik yang sarat kepentingan.
Argumen bahwa energi nuklir merupakan jalan strategis menuju kemandirian energi memang menggoda.
Akan tetapi, dalam konteks Indonesia, pendekatan ini justru berpotensi menghadirkan persoalan baru yang lebih besar.
Pembangunan satu unit reaktor PLTN dapat menelan biaya miliaran dolar Amerika Serikat, sementara kemampuan fiskal nasional masih terbatas dan banyak sektor lain yang lebih mendesak untuk dibiayai, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan terhadap teknologi dan bahan bakar dari luar negeri juga membuka peluang dominasi baru dalam sektor energi nasional.
Dari sisi keselamatan, risiko yang ditimbulkan PLTN tidak dapat diabaikan. Negara maju seperti Jepang pun masih menanggung dampak panjang dari tragedi Fukushima, padahal mereka memiliki sistem pengawasan dan teknologi yang jauh lebih maju.
Di Indonesia, dengan infrastruktur yang belum sepenuhnya siap dan manajemen risiko yang masih lemah, potensi bahaya akan jauh lebih besar.
Dalam konteks ini, diplomasi energi seharusnya berpihak kepada rakyat, bukan hanya menjadi ajang proyek bergengsi yang menjanjikan keuntungan bagi segelintir pihak.
Sementara itu, Indonesia memiliki sumber daya energi terbarukan yang melimpah.
Tenaga surya, angin, mikrohidro, dan biomassa bisa dikembangkan secara bertahap, terjangkau, dan ramah lingkungan.
Transisi energi bersih tidak harus melewati jalur nuklir yang mahal dan penuh risiko.
Model energi terbarukan berskala kecil bahkan lebih sesuai dengan karakter geografis kepulauan Indonesia yang tersebar dan beragam.
Bahkan fakta terbaru menunjukkan bahwa udang dan cengkih asal Indonesia dikembalikan oleh Amerika Serikat karena terpapar radioaktif Cesium-137 (Cs-137).
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran baru di masyarakat, terutama di Bangka Belitung yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan PLTN. Jika sumber pangan saja bisa terpapar radioaktif, bagaimana nasib masyarakat Babel bila PLTN benar-benar beroperasi di wilayah mereka?
Di tengah derasnya promosi nuklir, muncul dugaan bahwa sebagian kegiatan dan kampanye pro-PLTN dijalankan melalui pola framing berbayar.
Sejumlah sumber menyebut adanya penggunaan mahasiswa dan mahasiswi untuk menggiring opini publik agar seolah-olah dukungan terhadap PLTN datang secara alami dari kalangan intelektual muda. Dalam beberapa kegiatan, oknum mahasiswa diduga diberi insentif berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp1.000.000 untuk menyuarakan narasi positif mengenai PLTN melalui forum dan media daring.
Salah satu sumber yang memahami pola komunikasi publik proyek tersebut mengungkapkan adanya indikasi pola framing terencana dalam penyebaran opini pro-PLTN di ruang digital.
“Polanya terlihat rapi. Ada koordinasi antara pihak penyelenggara, pengelola media, dan kelompok mahasiswa. Mereka diarahkan untuk menulis dengan nada yang seragam—menekankan kata energi bersih, masa depan hijau, dan kemandirian nasional. Kalimatnya hampir identik di beberapa media,” ujar seorang sumber yang enggan disebutkan namanya ini.
Menurut sumber itu, pola seperti ini bukan hal baru dalam praktik komunikasi proyek besar. Opini publik dibentuk melalui pendekatan halus: kampanye edukatif yang dikemas seolah-olah ilmiah dan objektif, padahal di baliknya terdapat arahan naratif yang kuat.
“Sebagian tulisan itu muncul hampir bersamaan di sejumlah platform lokal dan nasional. Kami menemukan pola waktu publikasi yang berdekatan dan kesamaan struktur paragraf. Ini mengindikasikan adanya desain komunikasi yang bersifat sistematis,” tambahnya.
Sumber lain dari kalangan mahasiswa juga mengaku pernah ditawari untuk mengikuti pelatihan dan menulis artikel tentang “energi nuklir masa depan” dengan imbalan tertentu.
“Awalnya saya kira kegiatan kampus biasa. Tapi setelah dijalankan, ternyata ada arahan tema dan sudut pandang yang harus kami angkat. Istilahnya ‘mengedukasi masyarakat’, tapi arahnya jelas ke dukungan PLTN,” ujar seorang mahasiswa yang meminta namanya disamarkan.
Citra mahasiswa yang dikenal cerdas, idealis, dan dipercaya publik menjadi modal efektif untuk membangun kesan bahwa proyek nuklir mendapat dukungan dari generasi terpelajar.
Narasi seperti “energi bersih”, “ramah lingkungan”, dan “simbol kemajuan bangsa” disuarakan secara masif tanpa memberi ruang bagi kritik.
Jika dugaan tersebut benar, maka telah terjadi pergeseran nilai yang serius.
Mahasiswa yang seharusnya menjadi pengontrol kebijakan publik justru diarahkan menjadi alat legitimasi kepentingan ekonomi dan politik tertentu. Faktanya, banyak warga Bangka Belitung justru menolak rencana pembangunan PLTN, seperti yang terlihat dalam aksi “Rembuk Kampung” warga Beriga beberapa waktu lalu.
Manipulasi opini melalui kalangan muda bukan hanya persoalan komunikasi, tetapi juga mencerminkan krisis etika publik. Dunia kampus dan organisasi mahasiswa sejatinya merupakan ruang berpikir bebas dan independen.
Bila kegiatan yang mengatasnamakan edukasi ternyata disponsori oleh pihak berkepentingan tanpa transparansi, maka ruang akademik kehilangan integritasnya.
Setiap kegiatan yang melibatkan mahasiswa seharusnya terbuka mengenai siapa penyelenggara, siapa pemberi dana, dan apa tujuan sebenarnya dari program tersebut.
Tanpa keterbukaan itu, publik akan sulit membedakan antara pendidikan energi dan propaganda energi.
Kedaulatan energi sejati tidak diukur dari siapa yang membangun reaktor, melainkan dari siapa yang mengendalikan kebijakan dan arah pembangunan energi nasional.
Bila opini publik dibentuk melalui framing, bayaran, dan riset yang difasilitasi oleh pihak berkepentingan, maka kedaulatan itu telah hilang sejak awal.
Indonesia membutuhkan keputusan yang jernih, berbasis data, serta berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan pada ambisi proyek atau tekanan politik tertentu.
Energi nuklir memang memiliki daya tarik dan potensi besar, tetapi sebelum berbicara tentang reaktor dan diplomasi energi, bangsa ini harus lebih dulu memastikan transparansi, integritas, dan kemurnian proses pengambilan kebijakan. Kritisisme publik, terutama dari kalangan muda dan mahasiswa, harus dijaga agar tetap independen dan tidak mudah diarahkan oleh kepentingan sesaat. Sebab, pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan bukan sekadar masa depan energi, melainkan masa depan kesadaran bangsa. (JB)